OPINI HERMAN YOSEPH FERNANDEZ (Catatan Perjuangan Pemuda Pelajar Soenda Ketjil asal NTT dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949) 18 Dec 2024 21:35
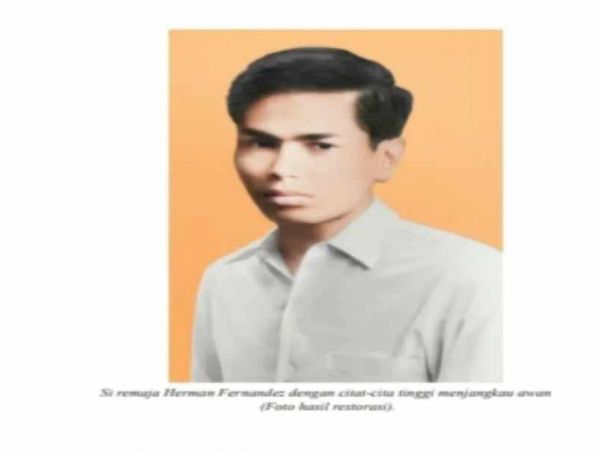
Bagaimanapun, pengakuan negara bagi pahlawan nasional adalah sebuah keputusan politik yang pada akhirnya menjadi prerogasi Presiden.
Oleh : GF Didinong Say*
Kesadaran Republikan
Perjuangan para pemuda pelajar Soenda Ketjil asal Nusa Tenggara Timur (NTT), ikut mempertahankan kemerdekaan negara proklamasi Indonesia melawan pendudukan kembali Belanda, merupakan suatu realitas faktual historis.
Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa, muncul kebanggaan rakyat Indonesia terhadap eksistensi negara yang terbebaskan dari penjajahan.
Maka kehadiran Belanda kembali dalam topeng Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang mendompleng Sekutu dan hendak berkuasa kembali itu segera memantik reaksi perlawanan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa.
Gerakan rakyat mempertahankan kemerdekaan itu disebut sebagai perjuangan revolusi kemerdekaan yang terjadi dalam kurun masa 1945-1949.
Gerakan revolusioner mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia itu dilatari oleh suatu prinsip perjuangan.
Prinsip yang mengandung kesadaran bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan martabat sekaligus cita cita.
Oleh karena itu setiap warga republik harus siap untuk berjuang dan berkorban demi mempertahankan kemerdekaan tanah tumpah darah dari upaya penjajahan kembali. Itulah kesadaran republikan yang menjiwai setiap gerak langkah perjuangan para pahlawan.
Dalam perpektif sosio-historis, keberpihakan para pemuda pelajar pejuang Soenda Ketjil asal NTT kepada republik di masa revolusi itu merupakan suatu pilihan sikap yang kontroversial.
Sebagai suatu pilihan, a matter of choice, tentu tidak mudah bagi para pemuda pelajar pejuang asal NTT itu untuk mengambil sikap berbeda, posisi via a vis untuk berperang melawan pihak Belanda.
Bagaimanapun, Belanda selama itu merupakan patron atau panutan (baca : guru, meneer, pastor, pendeta) yang telah mendidik, membentuk visi dan idealisme serta cita cita dan tujuan hidup mereka.
Dengan demikian, pilihan untuk menjadi republikan bagi pemuda pelajar pejuang Soenda Ketjil asal NTT itu tentu melewati proses perubahan mental and mindset yang mendalam dengan sejumlah pertimbangan rasional objektif kritis maupun diskresi moral etis tertentu berdasarkan pengalaman dan realitas yang dihadapi di masa itu. Menjadi republikan itu bukan sekedar spontanitas, oportunis, terpaksa, apalagi ikut-ikutan saja.
Dengan kata lain, resistensi terhadap upaya kolonisasi kembali oleh Belanda dalam diri pemuda pejuang asal NTT itu merupakan suatu sintesa atau buah pencerahan kesadaran dialektis tentang makna kemerdekaan dan masa depan peri kehidupan bersama, berbangsa bernegara dengan segala konsekuensinya.
Dialog di antara Pater Adrianus Conteriuz, SVD, anggota delegasi Parlemen NIT yang sedang berkunjung ke Jogya Mei 1949 dengan para pemuda pejuang asal Flores di Tegalpanggung, cukup menjelaskan tentang kedalaman kesadaran republikan para pemuda pejuang itu.
Pater Adi bertanya, "Mengapa dan untuk apa kamu setia pada republik dan mau menjadi anjing Soekarno?"
Maka Seda, yang paling kritis di antara mereka menjawab: "Pater, kami lebih memilih merdeka bersama republik daripada menjadi inlander terjajah, karena di dalam kemerdekaan itu ada kebebasan, kesejahteraan dan keadilan."
Dalam situasi yang berbeda, Herman Yoseph Fernandez, di depan hakim pengadilan militer Belanda, dihadapkan dengan pilihan sulit; memilih menyangkal membunuh kapten Belanda dan dibebaskan, atau tetap bertahan dengan kesaksian bahwa dirinyalah yang menembak kapten Nex hingga tewas, lalu ia harus menerima vonis eksekusi mati.
Herman Yoseph Fernandez lantas menjawab, "Toean Hakim Yang Mulia, yang kami kenal dan kami bela cuma satu, Negara Republik Indonesia", Jogya, Desember, 1948.
Pelabuhan Ende, Agustus 1940
Sore itu, Waikelo, kapal pengangkut ternak nampak bergerak perlahan keluar meninggalkan pelabuhan Ende ke arah matahari tenggelam. Raut wajah lima penumpang remaja tanggung usia sekitar 15 tahun yang berdiri di sudut buritan kapal itu mencuatkan kesedihan.
Memandang ke daratan, segala memori suka duka tinggal di internaat Schakelschool Ndao, Ende selama lima tahun, 1935-1939, sekejab terbayang kembali.
Ndao adalah tempat terindah penuh kenanga; di mana mereka bersekolah, belajar, berdoa, dan bermain bersama dalam bimbingan Pater van Lersel, tuan guru Pederico, tuan guru Monteiro, dan lain-lain. Tanpa terasa ada butiran air mata yang jatuh.
Hari itu, lima lulusan Schakelschool 1939 ini melarat ke negeri Jawa untuk melanjutkan pendidikan.
Herman Yoseph Fernandez, Frans Seda, Silvester Fernandes, dan Willem Wowor, akan masuk pendidikan keguruan di HIK Muntilan.
Sementara Helena Pareira, gadis manis berambut ikal asal Maumere akan masuk pendidikan keputrian di Mendut.
Berselang satu jam kemudian, kota Ende sudah lenyap di balik horizon. Gunung Iya nampak tinggal pucuknya di kejauhan.
Setelah mentari terbenam, langit di laut selatan Flores yang tadi kuning kecoklatan dengan cepat berubah hitam menggelap. Namun hanya sebentar saja kegelapan itu karena di sekujur langit dari ufuk ke ufuk menyeruak sinaran bintang gemintang dalam jumlah bak pasir di pantai.
Di atas palka Waikelo, Herman Fernandez dan kawan kawan rebah berbaring, memandang takjub ke arah langit bertabur bintang itu.
Dalam pesona lukisan indah langitan malam itu, diiringi deburan ombak gelombang laut, tetiba terngiang kembali kata kata magis menghipnotis dari seorang tuan, orang boeangan yang pernah tinggal di kawasan Ambugaga kota Ende.
Orang boeangan yang selalu berpakaian necis deftek yang bernama toean Soekarno. Ia diasingkan dari Jawa. Ia pernah beberapa kali mengunjungi Schakelschool Ndao, sekedar mampir pesiar atau ijin pada Pater van ersel untuk bercakap-cakap dengan para siswa di depan kelas.
Biasanya didampingi pastor Huitink dari gereja Katedral Ende.
Suara toean Soekarno ketika berbicara di kelas itu sungguh lantang menggelegar memikat.
"Wahai kalian teruna-teruna Nusa Bunga. Camkanlah selalu dalam hati sanubarimu. Gantungkanlah cita-citamu setinggi-tinggi bintang di langit. Kejarlah ilmu pengetahuan sehebat-hebatnya. Terus belajar pantang menyerah. Berjuanglah sekuat-kuatnya. Karena nasib bangsamu kelak berada di atas pundak bahumu."
Schakelschool adalah sebuah sekolah lanjutan elit setingkat SMP yang pernah hadir di Flores dari tahun 1920-an hingga kedatangan bala tentara Dai Nippon ke Ende Flores, 1942.
Sejak tahun pertama pendidikan, seluruh proses belajar mengajar menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar. Holland sprechen menjadi lingua franca wajib sehari hari dalam lingkungan internaat.
Schakelschool itu diasuh oleh Missie Katolik. Pater van Lersel, SVD adalah penanggung jawab sekolah dan asrama, pembimbing, sekaligus guru beberapa mata pelajaran.
Durasi pendidikan lima tahun. Siswa Schakelschool adalah lulusan terbaik Sekolah Rakyat yang datang dari seluruh Flores. Kurikulum pelajaran di Schakelschool bermutu setara dengan standar sekolah umum lanjutan di Jawa. Pelajaran sejarah di Schakelschool itu tentang para pahlawan Belanda, sedangkan geografi adalah tentang peta Netherlands.
Schakelschool mungkin bisa disebut sebagai pabrikasi pemuda bumi putera agar kelak dapat menjadi klerk cakap di berbagai kantor onderafdeeling kolonial atau kantor swapraja di Flores.
Namun dalam agenda Misie Katolik, sesungguhnya siswa-siswa Schakelschool itu sedang dibentuk untuk menjadi awam Katolik Flores tangguh dan berpendidikan. Memiliki kemampuan bersaing dan siap membawa kemajuan masyarakat Flores kelak.
Sejarah membuktikan bahwa lulusan Schakelschool kemudian menjadi lapisan generasi terdidik pertama Flores yang menonjol dalam banyak bidang kehidupan, termasuk dalam hal politik dan kekuasaan serta pemerintahan di Flores untuk beberapa dekade selanjutnya.
Keunggulan kelompok eks Schakelschool Ndao itu antara lain adalah pada semangat korsa. Alumni Schakelschool Ndao dikenal senantiasa saling terhubung dan berjejaring, kompak dukung mendukung dan bekerjasama.
Hidup bersama 5 tahun di bawah satu atap tentu menciptakan ikatan batin yang kuat di antara segenap siswa Schakelschool itu. Mereka menjadi seperti sebuah keluarga dengan rasa persaudaraan yang kuat. Baku sayang, baku jaga, baku bantu adalah janji hati di antara mereka yang tak perlu terucap namun pasti dan nyata sepanjang hidup.
Maka walau kemudian harus hidup berpencar berbeda kota di Jawa, hubungan di antara para pemuda pelajar ini tetap terjalin melalui korespondensi surat menyurat saling berkabar.
Relasi yang intens juga dilakukan dengan beberapa senior Schakelschool Ndao yang telah lebih dahulu tiba di Jawa pada tahun sebelumnya.
Seperti dengan Laurens Say di Malang, Jan Huwa Gunas, Paulus Wangge dan Dion Lamuri di Jogya, John Loudoe, Karel Sadipun, Os Njoo di Surabaya, dan lain-lainnya.
Sejarah berkehendak lain. Perang Asia Pasifik pecah pada penghujung 1941. Bala tentara Jepang datang dan dengan cepat menguasai sekaligus memporakporandakan Indonesia.
Tiba tiba saja seperti sirna semua tatanan, mimpi dan harapan. Tiga tahun masa pendudukan Jepang menjadi masa yang gelap, vivere pericoloso bagi pemuda pelajar asal NTT itu. Para guru kulit putih ditangkap dan dimasukkan kamp interniran.
Sekolah dan asrama dijadikan gudang atau markas tentara dai Nippon. Para murid dipulangkan atau dibiarkan tercerai berai. Sungguh malang nasib pemuda pelajar perantauan dari NTT saat itu. Jauh dari kampung halaman, berkeliaran di Jawa di masa perang tanpa sanak keluarga.
Padahal, Herman Fernandez, Frans Seda, Silvester Fernandes di Muntilan sesaat sebelum pecah perang sesungguhnya sedang berada dalam lingkungan pembinaan diri terbaik oleh kolose Van Lith Muntilan. Namun semua buyar karena timbul perang.
Blessing in disguise, perang dan kehadiran Jepang justru pada akhirnya mempersatukan anak anak eks Ndao itu. Herman Fernandez memutuskan menjadi romusha di tambang emas Bayah Cikotok demi menyantuni teman temannya di Jogya.
Kelak setelah Jepang pergi 1945, ia bergabung ke Jogya. Seda, Silvester dan kawan-kawan lain dari Muntilan mengungsi ke Jogya menjadi loper koran atau kerja serabutan demi mempertahankan hidup.
Helena beruntung dapat diamankan para suster Mendut ke rumah sakit Panti Rapih Jogya, menjadi perawat, 1942.
Laurens Say yang beberapa tahun malang melintang di hutan hutan pulau Jawa di masa Jepang, 1946 menyusul bergabung ke Jogya.
Pada akhirnya, semua eks Schakelschool Ndao Ende menjadi orang Jogya. Seperti ada magnet kuat yang menarik mereka semua ke kota itu.
Kelak di markas Tegalpanggung Danurejan Jogya, 1946 dan seterusnya, anak-anak eks Ndao itu ternyata menjadi perwira perwira andalan dalam milisi Lasykar Soenda Ketjil, Batalion Paradja, TNI, yang tegak lurus kepada republik.
Panggung Awal Perjuangan
Pasca kekalahan Jepang dalam PD II, Agustus 1945, kekuasaan politik dan pemerintahan di Indonesia dianggap vakum.
Namun, sebagaimana konvensi perang internasional saat itu, kekuasaan politik atau pemerintahan di suatu wilayah pendudukan akan dikembalikan kepada statusquo atau dengan ketetapan Sekutu, selaku pemenang perang.
Setelah penyelesaian kasus Mallaby di Surabaya, November 1945, tentara Sekutu nampak mulai jenuh berperang dan ingin segera menyudahi petualangannya di Indonesia.
Seiring dengan pemulangan tawanan perang Jepang, Sekutu akan menyerahkan pengendalian keamanan dan ketertiban Indonesia kepada pihak NICA yang ikut menjadi bagian dari Sekutu dalam PD II tersebut.
Itulah momentum di mana Belanda melalui Gubernur Jenderal van Mook mulai berupaya menguasai kembali Indonesia dengan berbagai aksi penertiban polisionil, penataan sistem pemerintahan maupun aneka rekayasa politik dan militer lainnya.
Di Surabaya di masa awal kemerdekaan itu, dari peristiwa 10 November 1945, ketika kota itu digempur habis oleh Sekutu, beredar banyak kisah heroik tentang keberanian kalangan pemuda pelajar asal NTT.
Beberapa Catatan Sporadis
Frans Seda, Silvester Fernandes dan Herman Fernandez adalah tiga pemuda asal Flores yang karena persahabatannya dengan Aleks Rumambi asal Sulawesi semasa pendidikan di HIK Muntilan, sejak proklamasi 1945, lebih dahulu ikut bergabung dalam lasykar Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS).
Mereka sempat terlibat dalam beberapa pertempuran melawan Gurkha di Surabaya, dan Ambarawa, November 1945, sebelum hijrah ke Jogya.
Laurens Say, pemuda pelajar Flores lainnya di dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya itu sempat menyelamatkan Karel Sadipun dan beberapa keluarga asal Flores di Wonokromo dari mitraliur dan bombardir mustang Sekutu.
Selanjutnya, karena terhalang oleh blokade kapal perang Sekutu, alih-alih pulang ke Flores, ia justru memutuskan untuk menuju ke Jogya, bergabung dengan teman teman eks Schakelschool di sana, Desember 1945.
El Tari dan Ishak Tibuluji adalah dua kader sekolah pelaut di Tegal asal Sabu yang batal berangkat perang ke Jepang Agustus 1945. Keduanya terlibat dalam pertempuran singkat di front Semarang melawan Belanda, sebelum akhirnya meluputkan diri ke Jogya menjadi republikan, Januri 1946.
Amos Pah adalah nama seorang pemuda pemberani asal Sabu yang diketahui pernah ikut bertempur melawan Sekutu di Surabaya di selama bulan November 1945 dalam barisan arek-arek Suroboyo bersama kolonel Soengkono, Bung Tomo dan lain-lain.
Amos Pah merekrut sekelompok pemuda Sabu eks kelasi kapal di Tanjung Perak bersama puluhan buruh asal Sabu di pabrik gula dan perkebunan tebu di sekitar area Pasuruan dan Mojokerto, menjadi laskar rakyat dalam kesatuan BKR Surabaya.
Kesatuan ini dan itu dikisahkan nekat melawan pasukan Sekutu di kawasan Ngagel dan Pasar Turi. Seterusnya bertempur melawan Belanda di area Malang yang mengakibatkan banyak korban gugur tanpa nama dari antara kalangan pemuda Sabu tersebut.
Amos Pah dan sisa anggota kesatuan itu kemudian hijrah ke Jogya bergabung dalam Lasykar Soenda Ketjil, Batalion Paradja, TNI, 1946.
Konsolidasi kelompok pemuda Sabu dan Rote di Jawa di masa itu memang solid dan intens. Spirit perlawanan dan keberanian yang pernah dibangkitkan oleh kelasi Marthen Paradja asal Sabu di atas kapal De Zeven Provincien, Aceh 1931, agaknya sangat menginspirasi semangat mereka melawan Belanda di masa revolusi kemerdekaan.
Tonggak Penting
Menjelang akhir 1945, Sekarno Hatta dan pimpinan Republik Indonesia lain terpaksa pindah ke Jogya karena NICA Belanda sebagai bagian dari pemenang PD II telah mengambil alih Jakarta.
Belanda juga bergerak cepat untuk menguasai kembali wilayah eks Hindia Belanda lain yang tidak dapat melawan, ataupun dengan janji, politik devide et impera, membentuk negara boneka, maupun dengan tekanan militer.
Konflik bersenjata segera muncul di beberapa tempat seperti Jawa dan Sumatera karena rakyat dan kaum republikan melawan. Maka DK PBB memaksa kedua negara, Belanda dan Indonesia ke meja perundingan untuk menandatangani Perjanjian Linggarjati, Maret, 1947.
Indonesia memang mendapat keuntungan karena muncul pengakuan dan simpati internasional atas Perjanjian tersebut.
Namun setelah Linggarjati, Belanda ingkar dan terus beraksi sepihak menekan posisi Indonesia wilayah Indonesia dengan demarkasi dan operasi militer.
Tiga bulan setelah Perjanjian Linggarjati, 18 Juli 1947, van Mook mengeluarkan perintah agresi militer I demi menguasai semua potensi dan jalur ekonomi, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.
Kekuatan ekonomi Indonesia ingin segera dilumpuhkan. Namun api perlawanan rakyat dan militer Indonesia tak kunjung padam malah kian berkobar.
Pada akhirnya seluruh kekuatan militer Belanda memang terarahkan ke Jogya. Wilayah seputaran Jogya dikepung.
Pertempuran di berbagai front pertahanan republik di semua jalur ke arah Jogya seperti di Solo, Gombong, Kebumen Magelang, Wonogiri, semakin dashyat.
Atas desakan internasional muncul lagi resolusi DK PBB untuk perdamaian. Namun segala upaya diplomasi tersebut ternyata hanya menghasilkan kesepakatan gencatan senjata sementara, mediasi Komisi Tiga Negara, Perjanjian Roem-Roien ataupun Perjanjian Renville yang semakin merugikan Indonesia. Belanda justru kembali bersiap melancarkan Agresi Militer II ke Jogya dengan lebih masif.
Jenderal Spoor pimpinan militer Belanda merancang Kraai Operatie dengan metode blietzkrieg untuk merebut Jogya.
Operasi Gagak itu didukung sepenuhnya oleh Brigade Macan pimpinan Kolonel van Langen dari Semarang. Semua titik pertahanan republik sekeliling Jogya dihancurkan, Maguwo direbut dan pasukan Belanda langsung masuk ke Jogya, 19 Desember 1948.
Konvoi lapis baja Belanda di hari kemenangan itu melintasi Malioboro disambut meriah oleh kaum inlander oportunis dengan sorakan dan kibaran bendera Merah Putih Biru sambil menyanyikan lagu Wilhemus.
Tentara Belanda langsung menangkap dan mengasingkan Soekano Hatta beserta pimpinan negara lain keluar Jogya.
Namun kala itu, Jenderal Soedirman menolak menyerah. Ia tinggalkan Jogya dan mulai melancarkan aksi perlawanan gerilya dari hutan. Sementara itu, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia segera dibentuk.
Belanda ternyata lengah. Tanggal 1 Maret 1949, pagi hari benar, militer Indonesia didukung berbagai lasykar rakyat, milisi pemuda dan pelajar berhasil melancarkan aksi Serangan Oemoem 1 Maret 1949.
Kaum republikan sempat menguasai Jogya beberapa jam. Serangan balasan Indonesia ini sangat menguntungkan posisi Indonesia di mata internasional, membuktikan bahwa pemerintah dan militer Indonesia masih ada.
Ternyata propaganda Belanda bahwa pemerintahan Indonesia dan militer Indonesia sudah bubar itu palsu.
Maka DK PBB segera mendesak Belanda dengan lebih keras termasuk dengan ancaman penghentian bantuan Colombo Plan.
Atas Resolusi DK PBB, Konperensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda segera digelar di Den Haag, tanggal 21 November 1949 yang menghasilkan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia walau masih dalam konsep federalisme van Mook.
Soekarno Hatta dan pimpinan negara lainnya dipulangkan ke Jogya seterusnya kembali ke ibukota Jakarta.
Sejarah menjelaskan bahwa hanya butuh waktu satu tahun bagi Ibu Pertiwi untuk memangku kembali hampir semua negara boneka bentukan van Mook dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1950. Minus Papua.
Lasykar Soenda Ketjil, Batalion Paradja, TNI
Sejak awal 1946, kaum republikan mulai datang memenuhi Jogya, berkumpul di sekitar Soekarno Hatta dan pimpinan negara Indonesia yang untuk sementara beribukota di kota itu.
Di masa itu, lapisan para pejuang republikan yaitu tentara, rakyat dan pemuda pelajar republikan mulai mempersiapkan diri untuk melawan serangan militer Belanda dengan membentuk berbagai kesatuan reguler, barisan milisi pemuda pelajar, atau lasykar rakyat.
Lasykar Soenda Ketjil di Jogya dibentuk dan dipimpin oleh Herman Johaness dan kawan kawan. Lasykar ini kemudian diresmikan sebagai bagian dari batalion TNI dalam Divisi Ngurah Rai, 1947, yaitu menjelang operasi Agresi Belanda I dan II.
Pada pemuda pejuang Soenda Ketjil dengan demikian menjadi tentara resmi, dengan pangkat terendah letnan dua.
Di dalam lasykar Soenda Ketjil ini, para pemuda pelajar asal NTT secara khusus dilatih disiplin dan mental secara spartan dan dibekali pengetahuan perang, tenik dan strategi kemiliteran oleh Jos Kodiowa, eks Shodancho PETA.
Selain itu, patut dicatat bahwa para pemuda pejuang Soenda Ketjil asal NTT, khususnya dari Flores adalah pemuda putus sekolah karena perang namun memiliki semangat belajar yang tinggi.
Maka di setiap sore hingga malam hari, di antara 1946-1947, mereka selalu datang ke lingkungan Istana Sultan Jogya yang dijadikan pusat kegiatan sementara pemerintahan republik untuk mendengarkan ceramah dan pengajaran gratis dari para Bapa bangsa seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, Kasimo, dan lain-lain.
Para pemuda pelajar pejuang Soenda Ketjil asal NTT itu lalu secara khusus membentuk sebuah kesatuan dengan nama Batalion Paradja yang bermarkas di kawasan Tegalpanggung, Danurejan, Jogyakarta.
Batalion ini terdiri atas beberapa kompi yang sebagian besar anggotanya adalah para pemuda Sabu dan Rote.
IR Lobo, Jeremias Henuhili, Hendrik Rade adalah 3 nama terkenal asal Sabu dalam kompi berani mati Batalion Paradja tersebut.
Dalam upaya menahan laju gerakan Belanda menuju Jogya, Lasykar Soenda Ketjil, Batalion Paradja pernah ditempatkan di Front Wates, 1948.
Dengan tugas utama melakukan sabotase, perusakan pada infrastruktur akses transportasi dan komunikasi ke arah Jogya. Peledakan memang keahlian Herman Johaness perakit dinamit dari Akademi Militer Jogya seangkatan Soesilo Soedarman.
Dalam sebuah kontak senjata di Wates, Eltari tertembak di pangkal paha dan diselamatkan Hawoe Dima dan lain lain. Henuhili dan Hendrik Rade gugur di front Wates, itu, 1948. Dimakamkan di TMP Kusumanegara Jogyakarta.
Sebelumnya, atas ajakan Aleks Rumambi, sahabat dari HIK Muntilan yang terus bersama bekerja di tambang Bayah Cikotok semasa pendudukan Jepang, Herman Fernandez yang handal dan bertubuh kuat akhirnya diperbantukan sebagai pemegang Juki dalam kesatuan PERPIS pimpinan Maulwi Saelan di front Gombong dan Kebumen.
Ternyata dalam sebuah kontak senjata, Herman Fernandez terkepung dan tertangkap Belanda di front Sidobunder Kebumen, September,1947, ketika sedang membopong tubuh Aleks Rumambi yang sekarat.
Herman Fernandez kemudian dieksekusi mati melalui putusan pengadilan militer Belanda karena dianggap bertanggungjawab atas kematian Kapten Nex, pimpinan tentara Belanda di front Kebumen-Gombong, 90 km arah barat Jogya itu.
Jasad Herman Fernandez entah dikuburkan di mana, namun sebuah makam kosong dengan nisan bertuliskan nama Herman Fernandez diletakkan di TMP Kusumanegara, Jogya bertanggal 31 Desember, 1948.
Eulogi Jejak Nilai Perjuangan Herman Fernandez
Herman Fernandez adalah putra Senhor Markus Suban Fernandez yang adalah seorang guru sekaligus de rechtenhand van de pastoor.
Dalam diri Herman Fernandez sejak belia telah tertanam kuat prinsip bahwa pengorbanan diri bagi sesama (self sacrifice) merupakan wujud kasih dan pelayanan yang sehebat hebatnya.
Maka bagi Herman Fernandez, cita-cita tertinggi yang ia gantungkan pada bintang-bintang di langit adalah bagaimana agar dirinya dapat selalu melayani sesamanya, temannya, bangsa dan negaranya dengan sebaik baiknya bahkan dengan pengorbanan diri bila diperlukan.
Keberanian dan komitmen Herman Fernandez di Sidobunder ataupun di berbagai front pertempuran lainnya itu kiranya cuma bentuk ekspresi yang keluar dari jiwa republikan yang selalu siap berkorban.
Maka di titik paling krusial dalam kehidupannya, rasa sakit, lelah bahkan ancaman kematian sudah tidak tidak memiliki arti apa apa lagi.
Bagi Herman Fernandez, penderitaan hanyalah sekedar jalan pelepasan diri atas segala kefanaan dan keterbatasan dunia.
Dengan vonis eksekusi mati pada dirinya, maka akhir hidup yang seharusnya menjadi misteri justru menjadi shortcut yang diterima Herman Fernandez secara bahagia tanpa sedikitpun gelisah maut. Hati dan jiwa yang legowo seperti itu kiranya dapat menerima kematian dengan tenang.
Maka catatan perjalanan hidup Herman Fernandez itu ibarat selembar tabula rasa yang segera menjelma menjadi putih bersih kembali setelah dibubuhi tanda titik.
Selanjutnya, tabula putih bersih itu menjadi persembahan jiwa kusuma bangsa pemuda pejuang pemberani Lasykar Soenda Ketjil, Batalion Paradja, TNI, Letnan Dua, Herman Yoseph Fernandez bagi bangsa negara, rakyat Indonesia dan republik yang dijunjungnya.
Dengan demikian, pihak manapun yang menghargai pengorbanan bagi sesama sebagai nilai hidup utama kiranya boleh menuliskan kembali huruf, kata, dan kalimat, atau sekedar simbol dan pengakuan di atas tabula rasa nan putih bersih itu.
Pahlawan Nasional
Usulan gelaran bagi sosok Herman Yoseph Fernandez yang dieksekusi mati Belanda, 1948, dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu telah memenuhi semua persyaratan menurut peraturan dan perundangan, baik secara teknis maupun formal untuk dapat ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Herman Fernandez dimakamkan di TMP Kusumanegara Jogya. Catatan perjuangannya seperti Palagan Sidobunder di front Gombong Kebumen kini menjadi bagian dari dokumen sejarah militer Indonesia.
Banyak catatan dan testimoni dari teman seperjuangan Herman Fernandez seperti Maulwi Saelan, La Sinrang, Aleks Rumambi, dan lain lain tentang perjuangannya dalam buku Angkatan Bersenjata Indonesia.
Belum termasuk berbagai kisah romantisme perjuangan yang tidak tercatat (untold story) namun beredar di antara teman seperjuangan dari Batalion Paradja tentang aksi perang kota dan sabotase yang mereka lakukan bersama semasa pendudukan Belanda di Jogya.
Pada beberapa tugu monumen peringatan perjuangan Tentara Pelajar di Jawa Tengah tertera jelas nama Herman Fernandes sebagai salah satu kusuma bangsa yang menumpahkan darah demi tegaknya republik.
Di Larantuka Flores Timur, Frans Seda, Laurens Say, Silvester Fernandes, Ishak Tibuluji, dan para sahabat di Batalion Paradja mendirikan sebuah patung bagi Herman Fernandez.
Secara kompararatif, ada banyak narasi paralel heroisme pemuda pejuang usia muda yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional seperti Robert Wolter Monginsidi, Daan Mogot, dan lain-lain.
Bagaimanapun, pengakuan negara bagi pahlawan nasional adalah sebuah keputusan politik yang pada akhirnya menjadi prerogasi Presiden.
Prof. Asvi Warman Adam, peneliti sejarah LIPI pernah menjelaskan tentang beberapa fenomena kecenderungan diskresi atau pertimbangan politik dalam suatu proses penetapan gelaran pahlawan nasional.
Misalnya, pertimbangan gender, keterwakilan daerah, keterwakilan sektoral, keterwakilan agama, sampai dengan kepentingan elektoral belakangan ini.
Di balik basis pertimbangan atau tendensi politik dalam penetapan gelar pahlawan nasional bagi sosok berjasa asal Flores seperti Herman Yoseph Fernandez, Frans Seda, atau tokoh pejuang lain kelak, ada hal yang patut digarisbawahi.
Bahwasannya, NTT dan Flores khususnya yang hingga kini belum memiliki pahlawan nasional sendiri itu ternyata merupakan bagian integratif dari Indonesia, pemegang saham republik yang sah, anak kandung republik yang sejak awal ikut mempertahankan kemerdekaan, bahkan dengan meterai darah putera putera terbaiknya seperti Herman Fernandez itu.
* Penulis merupakan pemerhati sosial-budaya.













Komentar